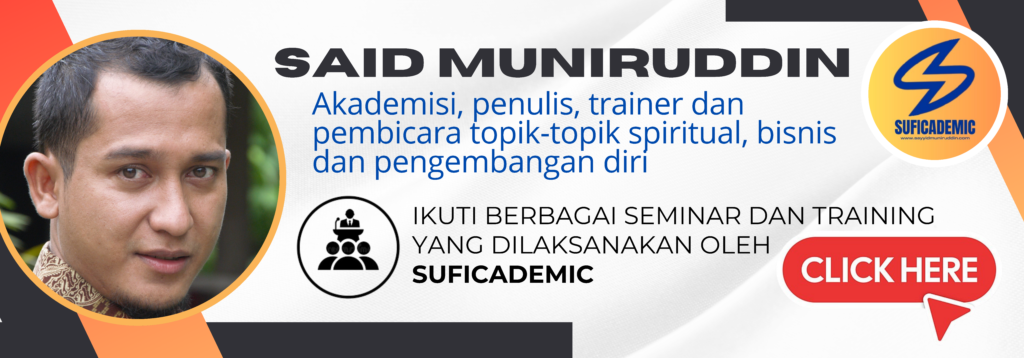
Jurnal Suficademic | Artikel No. 13 | Januari 2024
ALLAH TIDAK GAIB
Oleh Said Muniruddin | RECTOR | The Sudicademic
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. Kalau kita konsisten mengamati perkembangan agama Islam disepanjang zaman, akan ditemukan sebuah bukti lain yang tidak terbantahkan, bahwa Allah itu “tidak gaib”.
Begini. Maksud Allah “tidak gaib” adalah, Dia bisa ditemui. Ada interaksi yang dapat dibangun secara live dengan-Nya. Dia bisa diajak berbisik-bisik. Bisa diajak bercakap-cakap. Dengan-Nya, manusia bisa berkalam/berbicara secara langsung (Kalamullah). Ruh-Nya bisa dicerap/rasa (Ruhullah). Dengan-Nya, Anda bisa akrab (Khalilullah).
Faktanya adalah; nabi pertama berjumpa dengan Allah. Nabi terakhir saw juga berjumpa Allah. Semua nabi diantara mereka juga berjumpa Allah. Artinya, sejak awal sampai akhir zaman, Allah selalu bisa dijumpai. Sejak Adam yang mewakili generasi awal, sampai Muhammad yang mewakili generasi akhir zaman, Allah itu tidak gaib. Setidaknya, menurut sebuah hadis, ada 124.000 peneliti spiritual yang hidup antara era Adam dan Muhammad, yang bisa bertemu dengan Allah.
Sesuatu yang sudah ditemui, tentu sifatnya tidak gaib lagi. Tidak hanya Allah, semua wujud yang dipercayai sebagai rukun kegaiban dari iman (termasuk malaikat) pernah dilihat sama nabi dan orang tertentu lainnya. Artinya, bagi orang-orang yang pernah melihatnya, itu bukan barang gaib. Itu gaib bagi kita, yang hanya mendengar dan membaca ceritanya saja.
Bukankah Allah itu Gaib?
Jadi, kenapa pula dalam banyak ayat Allah disebut Maha Gaib? Apakah judul di atas tidak bertentangan dengan Al-Quran?
Benar. Kita tidak akan membantah Alquran. Allah itu “gaib”. Sama halnya dengan uang bagi orang miskin. Bagi orang miskin, uang itu sifatnya gaib. Orang miskin tidak pernah melihat uang. Bahkan sangat susah mendapatkannya. Mereka percaya, uang adalah anugerah yang hanya diperlihatkan kepada orang kaya. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk yang bisa berjumpa dengan uang. Hanya orang-orang terpilih yang bisa melihat uang. Itu keyakinan orang miskin. Mereka berkata begitu, karena mereka tidak tau bagaimana cara memperoleh uang. Sementara, bagi orang kaya, uang itu tidak gaib. Uang itu barang nyata (dhahir). Bagi orang kaya, uang adalah sesuatu yang biasa mereka lihat setiap hari.
Jadi, gaib atau tidak gaibnya uang, hanya masalah “metode” bagaimana cara memperolehnya. Lewat metode kerja tertentu, seseorang bisa mengakses uang yang maha gaib itu. Walau terkadang perlu mujahadah besar untuk memperolehnya.
Dengan Allah juga begitu. Bagi yang “miskin spiritual” (lemah metode), Allah itu gaib. Allah itu hanya “wujud hipotetis”. Allah dipercaya ada, tapi tidak bisa dijumpai. Sementara, bagi orang yang “kaya hati” (kuat metode), Allah itu maha nyata. Bisa ditemui. Telinga, lisan dan mata mereka bisa terkoneksi (rujuk) dengan-Nya (QS. Al-Baqarah: 18).
Jadi, disatu sisi sudah benar. Bahwa Allah itu “gaib” (wujudnya hipotetis, dipercaya ada). Mungkin kita termasuk orang yang masih bertuhan pada level ini. Meminjam kerangka ilmiah, kita masih bertuhan di Bab 2, masih dalam bentuk Kajian Teori dan Hipotesa. Sedangkan ahli makrifat sudah masuk ke ranah metode (“tarikah”). Itu ada di Bab 3. Hanya melalui sebuah metode yang robust, seseorang dapat menemukan berbagai esensi pengetahuan dalam aneka dimensi/hakikat. Biasanya dibahas di Bab 4 (“Temuan/Hasil”) dan disimpulkan di Bab 5 (“Makrifat”). Proses beragama harus se-ilmiah itu.
Penyebab Gaib atau Tidaknya Allah
Dari diskusi di atas, dapat disimpulkan, penyebab gaib atau tidaknya Allah ada dua:
Pertama, gaib atau tidaknya Allah muncul karena perbedaan dua konsep ketuhanan. Jika dikaitkan dengan Ontologi Ketuhanan, dalam “wujud azali”-Nya, Allah memang sesuatu yang maha misteri. Tidak serupa dengan apapun. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa di dengar. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa diajak berbicara. Sehingga tidak bisa dijangkau. Maha transenden. Jangan mencari Dia dalam wujud ini. Dia adalah “matahari” yang wujud mutlak-Nya tidak akan pernah terjangkau oleh mata inderawi. Kalau dipaksa untuk melihat, bisa buta, bisa gila kita.
Sementara, dalam “wujud tajalli”, Dia bisa diketahui. Dia juga wujud Cahaya, sebuah esensi yang terpancar langsung dan tidak pernah terpisah dari “matahari”. Dia, dalam wujud isyraqi, terpancar kemana-mana. Sehingga membentuk segala sesuatu. Dia hadir dengan ciptaan, dalam ciptaan, melalui ciptaan. Maha imanen. Dia ada, dimanapun engkau berada. Dia maha besar. Realitas-Nya maha meliputi, ada disegenap ufuk, juga di dalam diri. Dia bertajalli, termanifestasi dalam wajah rasul utusan-Nya.
BACA: “CERMIN ILAHI“; “TAUHID, DARI AHADIYAH KE WAHIDIYAH”
Kedua, gaib atau tidaknya Allah, tergantung penguasaan metode (tarikah) dalam beragama. Jika hanya bertumpu pada metode teks (bayan) dan argumen (burhan), Allah akan selamanya gaib. Dalam tradisi rasional, Allah itu hanya sebuah nama dari Wujud. Sementara, bagi mereka yang sudah mengaplikasikan teknologi perjalanan jiwa (irfan), akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Mata dari jiwa (bashirah) akan mengalami syuhud (penyaksian terhadap alam hakikat). Bahkan dalam terminologi lain disebut sebagai pengalaman keterintegrasian “jiwa” dengan “Jiwa”, atau leburnya “aku” dalam “Aku”. Disaat itu, Dia tidak lagi gaib.
Penutup
Agama adalah sebuah tradisi ilmiah paling kuno di dunia ini. Tugas penganutnya, sejatinya adalah melakukan research berulang-ulang, di setiap tempat dan zaman, untuk berjumpa dengan Allah. Sebab, Allah itu secara teoritis memang ada. Tapi perlu metode praktis untuk bisa mikraj/wushul (terkoneksi) dengan-Nya. Agama Islam tentu akan semakin ilmiah dan bernilai universal, ketika pengalaman perjumpaan dengan Allah yang dialami 124.000 orang shaleh terdahulu, bisa direplika oleh umat Muhammad di sepanjang masa. “Pasti bisa, kalau kita menggunakan metode yang sama”, kata Sufimuda.
Ingat, Islam itu “agama sempurna”, baik secara teoritis maupun metodologis. Secara konseptual, Alquran itu sempurna. Tidak ada cacat sama sekali dari segi isi Alquran. Pun secara metodologis, Muhammad saw mewarisi teknik-teknik yang sempurna dalam menjalankan riset spiritualnya, sehingga bisa berjumpa dengan Tuhannya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Itulah bentuk kesempurnaan Islam, sebuah agama yang sudah ada sejak era Adam. Dan menjadi sempurna pada masa Muhammad. Bagaimana tidak sempurna, sejak Adam sampai Muhammad, Allah bisa diajak berbicara. Muhammad membuktikan, bahwa pengalaman perjumpaan masih bisa dilakukan!
Sebuah agama disebut sempurna (kaffah), ketika Tuhan dipercayai ada, dalam berbagai konsep rasionalnya. Apakah Dia itu “jauh”, “dekat” dan sebagainya. Sekaligus secara metodologis, Dia juga bisa dijumpai keberadaannya. Sehingga, Tuhan bukan “wujud takhayul” (hayalan) dan juga bukan “wujud cerita” (dongeng/legenda). Melainkan “maha nyata”. Islam versi ilmiah seperti itulah yang diwarisi para nabi, dari Adam sampai Muhammad, kepada masing penerusnya.
Karena itulah, beragama itu berat; kalau harus sampai pada level ilmiah. Pada level teoritis, imajiner dan takhayul, itu mudah. Untuk itu, agama pada level tinggi disebut sebagai proses “purifikasi” (tazkiyatun nafs). Yaitu, usaha untuk memurnikan pikiran dan mental manusia dari aneka konsep hipotetis dan imajinasi. Dengan menempuh sebuah metode, sehingga semua keyakinan/kepercayaannya itu dapat terverifikasi kebenarannya.
Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa Aali Muhammad.
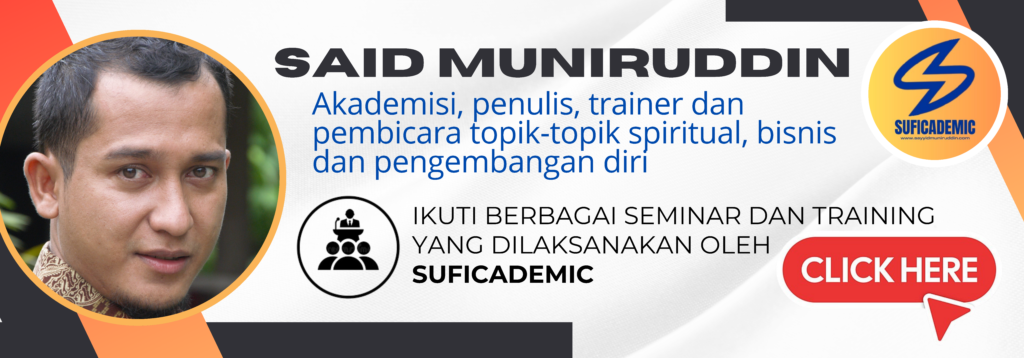
SAID MUNIRUDDIN | The Suficademic
Web: sayyidmuniruddin.com
TikTok: tiktok.com/@saidmuniruddin
IG: instagram.com/saidmuniruddin/
YouTube: youtube.com/c/SaidMuniruddin
Facebook: facebook.com/saidmuniruddin/
Facebook: facebook.com/Habib.Munir/
Twitter-X: x.com/saidmuniruddin
Channel WA: The Suficademic
Join Grup WA: The Suficademic-1
Join Grup WA: The Suficademic-2



**mitolyn**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.