Jurnal Suficademic | Artikel No.7 | Juli 2025
BERAGAMA TANPA BERTASAWUF, BERTASAWUF TANPA GURU: BISAKAH?
Oleh Said Muniruddin | Rector Suficademic
Bismillahirrahmanirrahim.
Sebenarnya banyak orang yang ingin bertasawuf. Tapi tanpa harus ‘diperantarai’ oleh guru mursyid. Takut syirik. Mereka ingin berhubungan langsung dengan Allah, tanpa dibimbing guru.
Iya, boleh. Beragama itu sebenarnya bebas aja. Kalau Anda bisa berhubungan secara langsung dengan Allah, go ahead! Bahkan, tanpa harus beragama sekalipun, kalau Anda bisa berhubungan langsung dengan Allah, juga silakan.
Tapi saya ragu, itu mustahil terjadi. Atau saat ini Anda sudah mampu berhubungan secara “interaktif” (langsung) dengan Allah?
***
Untuk menjawab ini, Anda harus mendefinisikan dulu agama itu apa, dan batasannya dimana. Agama itu kan tentang kepercayaan kepada Tuhan, cara menyembah dan kerinduan untuk berjumpa dengan-Nya. Hanya seputaran tiga hal itu.
Kalau batas beragama hanya sekedar untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, maka cukup beragama di level “tauhid” saja. Disini pun sebenarnya ada guru yang mengajari metode logika dan filsafat guna membangun kepercayaan secara benar. Agama pada dimensi ini adalah “akal” murni, levelnya basic sekali.
Tapi, kalau Anda ingin menyembah wujud yang Anda percaya, walaupun tidak tau Dia itu ada dimana dan seperti apa, maka batas beragama harus naik ke level “syariat”. Pada level intermediate ini, walau masih imajiner, Tuhannya jauh dan wujud-Nya hanya sebatas konsep (nama dan sifat), tapi sudah ada usaha untuk menyembah-Nya. Dalam urusan ini juga ada guru yang mengajari teori dan tafsir terhadap aneka dalil, teks, hukum dan konsep-konsep. Juga ada guru yang mengajarkan praktik-praktik dasar penyembahan (keislaman). Jadi, syariat itu masih level “akal” yang coba dipraktikkan oleh anggota tubuh.
Sementara; kalau Anda ingin rujuk, dekat, terhubung, berjumpa atau terkoneksi secara “langsung” dengan Allah -sehingga kepercayaan dan praktik penyembahan punya vibrasi atau rasa, Anda wajib bertasawuf. Dalam hal ini, juga ada guru yang mengajarkan metode (tariqah) guna menempuh perjalanan menuju Allah (tazkiyatunnafs serta sayr wa suluk). Pada tahap advance ini, akal dan anggota tubuh harus disingkronkan secara langsung dengan elemen “ilham” (getaran ruh/jiwa/qalbu).
Jadi, via bimbingan gurulah semua wujud ontologis dari pengetahuan bisa lebih objektif dan sempurna diperoleh. Memang kita punya kitab, akal dan hati. Tapi posisi guru sangat sentral dalam memaksimalkan fungsi teks, akal dan hati; sehingga kebenaran bisa maksimal diketahui, dijumpai dan dipraktikkan.
***
Pertanyaannya, “Bisakah beragama atau bertasawuf tanpa bermursyid?”
Jawabannya kembali pada tiga pilihan di atas. Tasawuf itu tentang ihsan (kebaikan). Kalau sekedar ingin percaya kepada kebaikan, Anda cukup bertasawuf pada level filosofis. Mungkin tak perlu guru. Cukup hanya dengan mengandalkan pikiran sendiri, membaca buku atau kitab tasawuf secara mandiri, Anda sudah bisa menerka tentang kebaikan. Tapi, kalau ingin mempraktekkan adab-adab tasawuf secara praktis, disini mulai berlaku sosok guru atau ‘nabi’ sebagai pusat pendidikan akhlak.
Apalagi kalau sampai pada level menempuh jalan sehingga bisa kembali (rujuk), bertemu (liqa), terhubung atau terkoneksi (mikraj) secara “aktif” kepada Allah; memangnya bisa tanpa guru? Karena, pada level ketiga ini, tanpa Pembimbing/Guru (nanti akan kita sebut sebagai “Cahaya”), kemungkinan kita akan tersesat dalam perjalanan panjang yang gelap gulita. Ujungnya pasti bersetan.
Semua ilmu dan praktik keagamaan yang tidak melalui proses “berguru” (dalam makna sufistik), hampir bisa dipastikan bersetan. Lihat saja. Banyak dari kita yang ketika semakin tau sesuatu, semakin sombong. Bahkan semakin kasar dan suka menuduh orang lain sesat atau salah. Meskipun dilakukan dengan cara-cara halus.
Agama, disatu sisi juga bisa membuat orang menjadi “tenang”. Tapi sifat tenang belum tentu menunjukkan bahwa keagamaan kita sudah benar. Sebab, untuk sekedar tenang, dengan mengkonsumsi narkoba juga bisa tenang. Dengan menghisap rokok juga bisa. Lewat meditasi juga mampu diperoleh rasa tenang itu. Tapi intinya bukan tenang. Melainkan “perjumpaan”, ridha dan diridhai.
Puncak keagamaan adalah “perjumpaan”, “pertemuan” atau “keterintegrasian” dengan Tuhan. Lewat cara itulah diperoleh tenang, bahagia dan ketercerahan yang sempurna. Sebab, tujuan puncak beragama adalah kembali kepada Tuhan (wushul illallah). Bukan sekedar percaya atau menyembah-Nya secara buta. Melainkan bermakrifat kepada-Nya. Mengenal, dekat, berjumpa dan merasakan kehadiran-Nya. Lewat makrifat inilah Dia sempurna disembah. Itulah fungsi tasawuf, menjadi wushul lewat metode tariqah.
***
Ada orang yang menolak bertasawuf. Juga menolak bermursyid. Tanpa itu semua, ia merasa bisa berhubungan secara “langsung” dengan Allah.
Katakanlah, begini. Anda sekarang sudah beragama. Tapi tidak bertasawuf. Juga tidak punya mursyid. Pertanyaannya, “Apakah cara beragama Anda sekarang telah membawa Anda untuk mampu berhubungan secara langsung dengan Allah?”. Kalau iya, tak usah bertasawuf dan bermursyid lagi.
Tetapi, kalau kita tau bahwa saat ini kita belum mampu berinteraksi secara “langsung” dengan Allah, lalu bagaimana caranya? Apakah ada cara lain selaind ari yang kita praktikkan sekarang, yangbisa membawa kita lebih dekat dan mampu berhubungan secara “langsung” dengan Allah?
***
Sebelum menjawab itu, ada satu pertanyaan penting untuk terlebih dahulu dijawab: apa yang dimaksud berhubungan secara “langsung”?
Maksud berhubungan secara “langsung” adalah, adanya koneksi, interaksi ataupun komunikasi yang bersifat “live” antara Anda dan Tuhan Anda. Anda bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan pun berbicara kepada Anda, dan Anda bisa mendengarnya. Tuhan melihat Anda, pun Anda begitu. “Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak kulihat”, kata imam Ali kwh.
Pernah nonton “siaran langsung” piala dunia? Itulah yang disebut “live” (langsung). Anda melihat dan mendengar secara langsung sesuatu yang sedang wujud/terjadi di luar sana. Bahkan Anda bisa berbicara dengan mereka yang ada di lapangan sana, jika alatnya ada. Itulah “langsung”. Apa yang terjadi di luar sana, “langsung” kita lihat dan dengar disini.
Bisakah kita begitu dengan Tuhan kita yang ada ‘disana’? Kalau sudah bisa begitu, berarti kita sudah mampu berhubungan secara “langsung” dengan Tuhan. Kalau tau apa yang sedang dikatakan Tuhan di alam sama, bisa melihat Dia sedang apa di langit sana; berarti hubungan Anda dengan Tuhan sudah langsung.
Kalau tidak sampai begitu, berarti belum “langsung”. Sekedar mengkhayal bahwa hubungan kita dengan Tuhan bersifat langsung, boleh-boleh aja. Tapi yang namanya “langsung” itu bukan khayalan. Tapi kenyataan, yang benar-benar dialami dan rasakan. Contoh orang yang telah berhubungan “langsung” dengan Tuhan adalah para nabi. Mereka manusia biasa. tapi lewat metode tertentu bisa mendengar dan berbicara secara “langsung” dengan Tuhannya.
Kalau Anda sudah bisa seperti itu, berarti Anda sudah meniru nabi. Bukan berarti harus menjadi nabi. Tapi paling tidak, Anda sudah mentauladani cara nabi dalam bertuhan dan beragama. Dalam hal beragama, nabi bisa berhubungan “langsung” dengan Allah.
Kita harus ikut nabi. Bukankah Anda ingin berhubungan “langsung” dengan Allah, yang Anda yakini tanpa perlu perantara? Kalau iya, ikuti cara nabi, sampai bisa berhubungan “langsung” dengan Allah. Kalau belum sampai pada level itu, berarti hubungan kita dengan Allah belum “langsung”. Masih terhijab. Masih “off”. Masih buta. Masih tersesat. Masih menyembah “patung” (tuhan yang mati, tidak hidup). Masih syirik.
***
Nabi adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi mereka mengetahui cara berhubungan secara “langsung” dengan Tuhannya. Kita disuruh mengikuti atau mentauladani nabi. Supaya bisa berhubungan “langsung” dengan Allah.
Uniknya, semua agama, juga semua orang, mengaku menyembah Tuhan secara “langsung”. Ada yang menyembahnya di masjid. Ada juga yang menyembahnya di tempat lain seperti gereja, kuil, sinagog dan sebagainya. Semua merasa sedang menyembah Tuhan secara langsung. Padahal, Tuhan yang disembahnya itu tidak pernah dirasakan, dilihat, diajak bicara dan didengar secara langsung.
Kenyataannya tidak begitu. Tidak ada yang menyembahnya secara “langsung”. Kita semua masih “bisu, tuli dan buta”. Tidak ada yang terkoneksi dan mampu menyembahnya secara interaktif. Kita hanya berpura-pura, seolah-olah kita melihat Dia. Padahal tidak. Kita masih sebatas berbaik sangka. Bukan betulan berhubungan secara langsung atau nyata dengannya.
***
Lalu muncul pertanyaan. “Bagaimana cara melangsungkan hubungan dengan Tuhan?”.
Jawabannya sederhana. Untuk bisa “langsung”, harus ada ‘perantara’. Harus ada ‘media’. Sebab, kita sedang mengakses wujud yang berbeda, yang ada di alam sana. Harus ada teknologi yang menghubungkan kita dengan-Nya.
Bayangkan, untuk nonton bola secara langsung saja, Anda harus ‘diperantarai’ oleh perangkat tertentu. Anda butuh TV, satelit, camera dan sebagainya. Tanpa itu, tidak bisa. Tugas camera, satelit dan TV adalah menangkap dan menghadirkan wujud dalam bentuk gelombang cahaya dan suara, sehingga bisa Anda lihat dan dengar secara langsung dihadapan Anda.
Jadi, wajib ada ‘perantara’ untuk bisa berhubungan “langsung” dengan Allah SWT. Kita ini makhluk tak berdaya. Karena itu sepanjang zaman diutus para nabi. Nabi itu ‘perantara’, agar kita bisa berhubungan “langsung” dengan Allah. Nabi itu media, satelit dan TV-nya Allah SWT. Lewat merekalah Allah hadir kehadapan kita. Lewat merekalah Allah bisa dilihat, didengar dan diajak berbicara.
Iya, nabi itu sekilas makhluk fisik. Manusia biasa. Tapi mereka sebenarnya adalah “cahaya” -yang diutus dari alam sana. Karena itu mereka juga disebut “rasul”. Rasul artinya “utusan” dari alam sana. Alias pancaran cahaya dari alam Tuhan.
Karena itulah; setiap diam, kata dan perbuatan nabi sifatnya “suci” atau “maksum”. Karenanya semuanya film, manifestasi atau siaran “langsung” dari Allah swt. Apapun yang terbit dari nabi, itu hukum atau kebenaran mutlak. Kalau bukan Quran, pasti hadis. Karena nabi adalah wujud dari vibrasi, gelombang, siaran atau pancaran cahaya “langsung” dari sisi Allah swt. Karena itu para nabi disebut sebagai Ruh Allah atau Kalam Allah, yang disiarkan secara langsung melalui wadah fisik seorang manusia biasa (basyariah).
Jadi, Ruh nabi itu “cahaya” langsung dari Allah. Kalau Anda terkoneksi atau bersanad secara langsung dengan (ruh) nabi, berarti Anda terkoneksi dengan Allah. Muhammad dalam wujud fisiknya hanya seorang manusia biasa. Tidak boleh disembah. Bukan Tuhan dia. Tapi wujud fisiknya itu merupakan “pembawa cahaya”. Ada Nurullahnya. Ada Allah disana.
Karena itu ada yang mengatakan, nabi itu bukan “perantara”. Melainkan “pembawa wasilah” (wasilah carier). Pembawa cahaya Allah. Maka siapapun yang terintegrasi dengan ruhani nabi (Nur Muhammad), akan tersambung “langsung” dengan Allah.
***
Jadi, apakah kita memerlukan ‘perantara’ untuk bisa berhubungan dengan Allah?
Jawabannya, iya. Wajib. Kita tidak bisa melihat tanpa “gelombang” ataupun “cahaya”. Apapun yang Anda lihat di TV, itu sebenarnya yang Anda lihat hanyalah gerak dari cahaya. Cahaya itulah yang menjadi “wasilah” sehingga Anda bisa melihat. Sementara TV adalah ‘perantara’, atau lebih tepatnya “pembawa wasilah (cahaya)”.
Pun kalau Anda mendengar lagu di radio. Anda bisa mendengar lagu karena ada “gelombang”-nya. Gelombang itulah yang menjadi “wasilah” sehingga Anda bisa mendengar secara “langsung” lagu-lagu yang sedang diputar di alam sana. Sedangkan wujud fisik perangkat radio hanya sebagai “pembawa gelombang” (wasilah carier).
Jadi, Anda tidak bisa berhubungan secara langsung dengan segala sesuatu tanpa ‘diperantarai’ oleh gelombang atau cahaya. Bahkan, termasuk ketika Anda sedang melihat seseorang yang sedang berdiri di hadapan Anda. Percayalah, Anda hanya bisa melihat orang tersebut setelah adanya cahaya yang sampai ke mata Anda. Tanpa cahaya, tak ada yang terlihat. Cahaya itu adalah wasilah, atau perantara, antara Anda dengan sesuatu.
Nabi itu “Cahaya”, yang menyebabkan Anda bisa melihat, mendengar dan berhubungan langsung dengan Allah. Bahkan “Cahaya”-nya sangat batiniah. Sirr, halus sekali. Cahaya di Atas Cahaya. Kalau “Cahaya” ini bisa Anda akses ke dalam diri, sambil menutup mata sekalipun; Anda bisa melihat, mendengar dan merasakan kehadiran Allah.
Bahkan, manusia biasa sekaliber Muhammad bin Abdillah sekalipun; itu baru bisa melihat, mendengar dan berinteraksi dengan Allah setelah terkoneksi dengan “Jibril as” (sang Ruh, Wasilah, Pembawa Cahaya). Setelah bersanad dengan kekuatan cahaya dari sosok Jibril ini, barulah kemudian Muhammad bin “Abdillah” berubah menjadi Muhammad “Rasulillah”. Ketika sempurna kehadiran entitas Cahaya dalam diri Muhammad, ia pun kemudian menajdi “wasilah” bagi yang lain. Aati Sayyidinaa Muhammadinil wasiilata wal fadhiilahati sayyidina muhammadanil wasilata wal fadhilah. “Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadlilah” (doa setelah azan).
***
Konon kabarnya, “Cahaya” Tuhan ini tidak pernah padam. Cahaya ini hidup dan abadi disepanjang tempat dan zaman. Muhammad sang pembawa wasilah, secara fisik boleh terkubur dan wafat. Tapi ruhaninya hidup. Ruhaninya merupakan elemen Cahaya, dan itu bersanad, terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Begitulah cara Tuhan terus hadir disepanjang zaman, melalui ruhani para imam, wali dan utusan.
Diriwayatkan, kalau Anda menemukan para pembawa tongkat estafet dari “api”, “obor” atau “cahaya” Tuhan ini, Anda akan menemukan Tuhan. Karena itu dikatakan, makrifat adalah mengenal imam, walimursyid atau guru ruhani pada zamannya.
Dalam bahasa lebih halus, mereka bukan “perantara” antara Anda dan Tuhan. Melainkan “pembawa” Cahaya Tuhan. Sebuah Cahaya yang harus Anda tangkap, agar Anda bisa me-“langsung”-kan hubungan dengan Tuhan. Tanpa cahaya ini, Anda bisa saja rajin beribadah, tapi dalam keadaan “bisu, tuli dan buta; tidak pernah rujuk/terkoneksi langsung dengan Allah SWT”. Shummun bukmun ‘umyun fahum la yarji’un.
Ibadah itu mudah. Menemukan “Cahaya” yang sulit. Beragama tanpa nabi, berislam tanpa guru atau bertasawuf tanpa mursyid; itu sama dengan beribadah tanpa Cahaya. Tak ada energi. Tak ada vibrasi. Sebab, esensi peribadatan yang sesungguhnya adalah keterhubungan dengan gelombang Cahaya.
***
Ada orang yang takut bermursyid. Takut membayangkan wajah Gurunya. Takut syirik. Terkadang mereka lebih memilih untuk membayangkan alam semesta, yang dianggapnya sebagai bagian dari (kebesaran) Tuhan. Silakan saja. Itu pola beragama yang diperkenalkan kembali oleh seorang pemikir teologi Yahudi Eropa abad 17, Baruch de Spinoza (1632-1677).
Mungkin karena kehilangan kepercayaan kepada para pendeta, rahib dan rabi yang tidak trustworthy, maka spiritualitas mazhab Spinoza menolak visualisasi terhadap “sosok manusia”. Pengalaman kekristenan dan Yahudi memang cukup negatif pada era kegelapan. Terlalu banyak muncul “walid” (nabi/mursyid) palsu ditengah komunitas agama. Sehingga masyarakat menjadi terkebelakang. Sehingga ia menolak keberadaan para sosok manusia sebagai “wakil Tuhan” (Khalifatullah).
Ilmu meditasi moderen banyak yang bersanad ke Spinoza. Mazhab ini hampir serupa dengan Hinduisme. Cenderung bertuhan kepada “alam semesta” dalam usaha mencapai ketenangan. Alam semesta dianggap sebagai tajalli Tuhan. Dalam meditasi model ini, kita diarahkan untuk mengosongkan pikiran, atau menghubungkan diri hanya dengan “energi” alam semesta. Mazhab spiritual Spinoza yang dianut barat hari ini hanya menyerahkan dirinya kepada alam, kepada ruang kosong, ketimbang kepada para guru spiritual.
Sementara dalam tasawuf versi Quran, selain hadir di segala ufuk alam (Allah adalah cahaya langit dan bumi, QS. Annur: 35), Tuhan dalam wujud Cahaya di Atas Cahaya (QS. Annur: 35) sebenarnya lebih condong menghadirkan diri-Nya dalam qalbu para utusan. Langit, bumi dan gunung sebenarnya tidak kuat untuk menampung “amanat” (cahaya) Tuhan. Hanya qalbu manusia yang bisa. Karena itu, Islam dalam dimensi mistiknya lebih menekankan akan kehadiran sosok para utusan sebagai pusat visualisasi dari vibrasi energi ketuhanan.
Karena itulah, kiblat pada dimensi syariat adalah bangunan, candi batu (Kakbah). Dimensi lahiriah alamnya memang begitu. Sedangkan kiblat dalam dimensi tasawuf adalah qalbu, wajah batiniah para utusan Tuhan. Dalam hal beragama, sempurnanya kita berkiblat kepada keduanya. Menghadap ke Kakbah. Sekaligus memiliki Guru spiritual.
***
Suatu ketika, seseorang bertanya: “Saya sudah lama bertasawuf, tapi belum bisa mendengar, melihat dan berinteraksi secara langsung dengan Allah; saya belum mengalami yaqazah dan belum punya muraqabah. Saya belum mengalami keterjagaan dan keterbukaan spiritual. Kenapa ya?”.
Jawabannya. Itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin orang tersebut belum mengamalkan tasawuf dan adabnya secara sungguh-sungguh. Kedua, mungkin juga itu karena kecilnya Cahaya yang diperoleh dari guru tasawufnya. Butuh Cahaya yang kuat agar seseorang bisa sampai pada level “inniwajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal ardh”.
Ibrahim as itu bertasawuf, dari satu guru ke guru yang lain. Dari bulan, bintang, matahari dan seterusnya. Mungkin ada belasan, puluhan atau mungkin ratusan gurunya. Dari satu cahaya ke cahaya yang lain. Ada yang cahayanya redup. Ada yang cahayanya timbul tenggelam. Dia terus mencari. Mungkin sampai menemukan sosok seorang “khidir” atau “wali”, “karamallahu wajhah”, “Cahaya di Atas Cahaya”, pribadi yang bisa menteleportasi ruhaninya untuk sampai kepada Wajah Allah swt.
Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa Aali Muhammad.*****

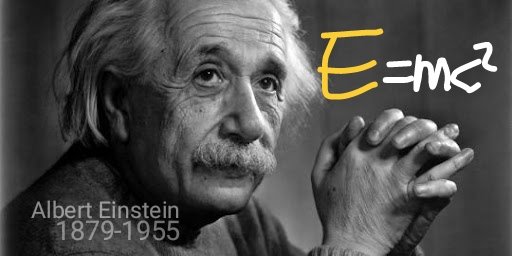

Dola789link – Seems like a decent spot to try your luck. Games load fast which is a plus in my book. Good selection too. Check ’em out! dola789link
Brazil calling for bet959br. Loads quickly, which is essential during live games and betting. Solid overall experience. Visit here: bet959br.
Hey! 888vi22vip is my go-to spot lately. It’s got a slick look and I’ve had some good luck there. Definitely worth checking out if you’re looking for a new place to play. Give 888vi22vip a try.
E aí, galera! Descobri esse tal de 2Q e fiquei curioso. Alguém já se aventurou por lá? Tem jogos legais? Me deem um feedback antes de eu me jogar de cabeça! Clica aqui: 2q
**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.