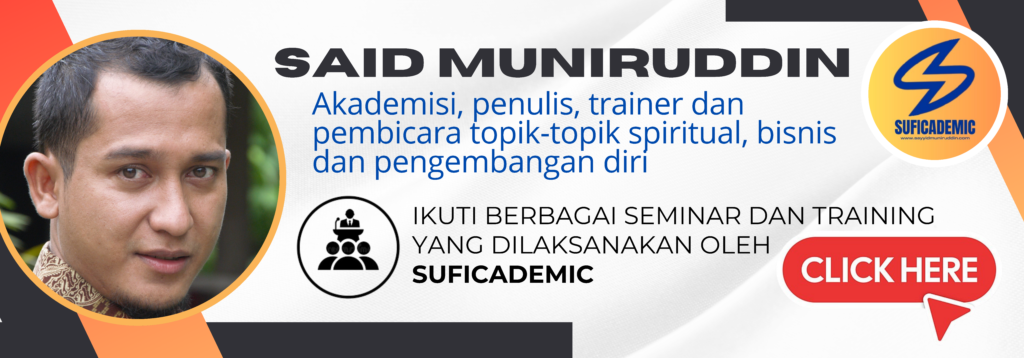
Jurnal Suficademic | Artikel No. 04 | Januari 2024
“IKHLAS”, KARENA ALLAH..
Oleh Said Muniruddin | RECTOR | The Suficademic
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. Jum’at pertama di awal tahun 2024. Di atas mimbar Masjid Al-Mizan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, sang khatib berbicara tentang “ikhlas”. Sebuah topik yang sebenarnya sangat sufistik.
Adalah Dr. Bismi Khalidin yang menyampaikannya, kebetulan juga tetangga kami dari kampung asal yang sama di Sigli, Aceh Pidie. Beliau sering menjadi imam, juga membuka pengajian untuk topik-topik fikih tertentu di masjid tersebut.
Saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan. “Ikhlas” adalah, bekerja karena Allah. Kali ini beliau kaitkan dengan kerja-kerja dalam membangun ekonomi Islam. “Membangun ekonomi Islam harus dilakukan secara ikhlas, harus karena Allah”, begitu inti khutbahnya.
Saya menyimak khutbahnya. Kelihatannya ada problem dalam pengembangan ekonomi Islam. Khususnya terkait ‘monopoli’ perbankan syariah di Aceh. Disatu sisi, hengkangnya bank konvensional dinilai sebagai kemenangan awal bagi pengusung ekonomi Islam. Disisi lain, Anda tau sendiri, monopoli dimana-mana melahirkan inefisiensi. “Cuma kita penyedia jasa di wilayah ini, bagaimanapun kinerja kita, ya tak ada pilihan lain bagi masyarakat kita”, bahasa selorohnya begitu.
Karena itu, kualitas pelayanan perbankan syariah dinilai belum maksimal. Bahkan masih buruk. Ketika ATM bank syariah tertentu selalu “minta maaf”, masyarakat tidak punya pilihan. Selain bersabar. Kalau terus menerus seperti itu, maka boleh dikatakan, semua yang dikerjakan itu “tidak ikhlas”. Khutbah tersebut merupakan harapan agar kualitas layanan bank syariah diperbaiki. Jika tidak, kemenangan ekonomi syariah adalah kemenangan yang nisbi, riya’.
Apa yang disampaikan DR. Bismi Khalidin di atas adalah “ikhlas” dalam bentuknya paling sederhana. Dalam artian, tulus dan sungguh-sungguhlah dalam bekerja.
Tingkatan Ikhlas
Saya ingin mengulas sedikit lebih luas. Sekaligus ingin menantang kita semua, untuk menyadari, bahwa ikhlas itu, realitas hakikinya, sebenarnya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sebab, apa yang selama ini kita sebut sebagai “ikhlas”, seringkali tidak lebih dari nafsu dan keinginan kita, yang kita persepsikan sebagai keinginan atau sesuatu yang disukai oleh Allah. Sementara, kita tidak pernah tau, apakah Allah benar-benar suka dengan apa yang kita kerjakan. Semua hanya persepsi kita saja.
Bayangkan, ada mujahidin yang “ikhlas” meledakkan tubuhnya di keramaian. Kalau tidak ikhlas, tentu tidak ada yang mau mati dengan cara itu. Dia menganggap, Allah senang dengan tindakannya itu. Menurut Anda, apakah itu sebuah tindakan yang “ikhlas” dilakukan karena Allah?
Sekelompok ulama, dengan sungguh-sungguh dan sangat “ikhlas” bermujahadah. Lalu lahirlah fatwa, bunga bank bukan riba! Sebutlah itu para ulama di Al-Azhar, Mesir. Menurut Anda, apakah mereka betul-betul ikhlas? Apakah yang mereka lakukan itu karena Allah? Apakah Allah ridha dengan kesungguhan mereka dalam melahirkan fatwa semacam itu?
Sekelompok ulama lain juga tidak mau kalah. Dengan “ikhlas” berfatwa, bunga bank adalah haram. Katakanlah, itu ulama di tempat kita. Apakah betul fatwa di negeri kita dibuat karena Allah dan disukai oleh Allah?
Siapa yang bisa memastikan, dari dua fatwa di atas, mana yang betul-betul menyenangkan Allah? Yang mana yang benar-benar karena Allah dan benar-benar diridhai Allah. Fatwa mana yang benar-benar sesuai kehendak Allah?
Jadi, “ikhlas” itu apa? Pertama, apakah ikhlas itu hanya PERSEPSI kita saja bahwa Allah senang dengan sebuah keputusan/tindakan yang kita ambil? Atau, “ikhlas” adalah sebuah keputusan/tindakan yang kita ambil MUTLAK sesuai keinginan Allah?
Keduanya benar. Keduanya adalah bentuk dari “ikhlas”. Hanya saja, tingkatannya berbeda.
Ikhlas model pertama adalah “ikhlas perseptif” (rasa/pengetahuan subjektif). Ikhlas ini berkembang luas dalam dunia syariah. Sesuatu dianggap sesuai dengan harapan Allah (diridhai/disenangi Allah), tapi sebenarnya murni berdasarkan pengetahuan/persepsi orang itu sendiri. Dia tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Allah, apakah Allah senang atau tidak dengan sebuah sikap yang dia ambil. Hanya dia sendiri yang merasa, atau berbaik sangka, bahwa Allah senang dengan itu. Anda bisa saja melakukan nom bunuh diri, setelah mengkaji dalil-dalil agama tertentu. Menurut Anda mungkin itu baik sekali, dan Anda akan melakukan tindakan itu dengan “ikhlas”. Tapi, apakah Allah senang? Apakah itu benar “karena keinginan Allah”?
Bentuk ikhlas kedua disebut “ikhlas konfirmatif” (rasa/pengetahuan yang objektif). Inilah bentuk ikhlas pada level hakikat. Artinya Al-Haqq sendiri yang langsung mengkonfirmasi, apakah sebuah tindakan/keputusan yang akan kita ambil benar-benar menyenangkan Dia, ataupun sebaliknya. Silakan melakukan suicide bombing, kalau setelah Anda tanyakan kepada Allah, Dia pun rela dengan tindakan Anda itu. Jika ia tidak suka, hentikan segera. Jangan menghayal, bahwa apa yang baik dan benar menurut persepsi Anda, itu baik menurut Allah. Sebab, “ikhlas” adalah, melaksanakan apapun yang disukai Allah. Walaupun kita sendiri mungkin tidak suka.
Penutup
Karena itu, “ikhlas” harus diupdate. Dari level “persepsi” (subjektif) ke level “konfirmasi” (objektif). Karena itulah, jalan dalam beragama dan memahami keinginan-keinginan Tuhan juga bertingkat. Dari syariah yang “teoritis-argumentatif”, sampai ke makrifah yang “mukasyafah-iluminatif”.
Ketika Anda memutuskan bahwa bunga bank adalah halal, ataupun haram, itu “ikhlas” berdasarkan argumentasi Anda tentang kebenaran; atau memang Tuhan telah datang kepada Anda untuk menyetujui bahwa itu adalah kebenaran?
Itulah pesan yang Dr. Bismi Khalidin ingin sampaikan. Kita sepakat, harus ikhlas. Membangun ekonomi Islam harus ikhlas. Sebab, ekonomi adalah sebuah arena penuh keputusan dan tindakan. Harus dijalani dengan ikhlas. Pertanyaannya, “ikhlas” pada level mana yang bisa kita bangun? Apakah ikhlas sesuai persepsi dan ego kita yang sangat halus itu? Atau sesuai bisikan-bisikan yang lebih tinggi (ilham) yang disalurkan secara langsung dari sisi Tuhan?
Dari sini kita sebenarnya harus paham. Selama seseorang belum sampai kepada Tuhan (belum makrifat), ikhlas itu tidak pernah ada secara hakiki. Semua yang kita sebut ikhlas, sesungguhnya hanyalah ketulusan berdasarkan daya nalar filosofis kita sendiri, merasa bahwa apa yang kita lakukan baik menurut Allah. Padahal belum tentu. Ikhlas kita sifatnya sangat spekulatif. Karena itu, belum tentu hal yang kita persepsikan sebagai “baik”, itu diterima Allah. Sebab, Dia hanya menerima amalan yang “ikhlas”, yang secara hakikat menyenangkan-Nya, yang sesuai keinginan-Nya.
Ikhlas, secara hakiki, terjadi pada saat wujud ruhani dan kehendak manusia menyatu dengan Allah. Ikhlas, dalam bentuknya yang sempurna, terjadi manakala wujud gerak dan keinginan kita merupakan manifestasi (tajalli) dari yang Ahad. Qul huwallahu Ahad! (Qs.Al-Ikhlas: 1). Ikhlas adalah wujud keinginan dan tindak tanduk manusia, yang menjadi cerminan dari berbagai kehendak Ilahi. Ikhlas adalah kemampuan menghilangkan “diri”, dan membiarkan Tuhan yang bekerja (taslim/pasrah). Ikhlas adalah keterintegrasian antara kemauan langit dengan bumi. Ikhlas adalah kehadiran Allah dalam diri. Ikhlas adalah: “dari Allah, oleh Allah, dan hanya untuk Allah”.
Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa Aali Muhammad.
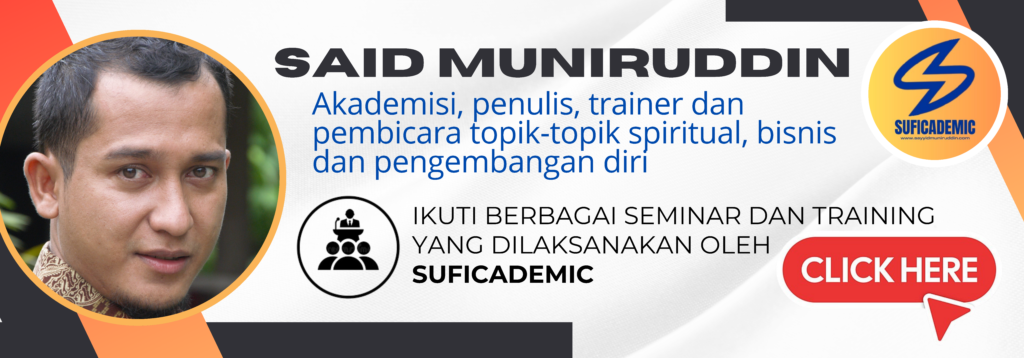
SAID MUNIRUDDIN | The Suficademic
Web: sayyidmuniruddin.com
TikTok: tiktok.com/@saidmuniruddin
IG: instagram.com/saidmuniruddin/
YouTube: youtube.com/c/SaidMuniruddin
Facebook: facebook.com/saidmuniruddin/
Facebook: facebook.com/Habib.Munir/
Twitter-X: x.com/saidmuniruddin
Channel WA: The Suficademic
Join Grup WA: The Suficademic-1
Join Grup WA: The Suficademic-2



Terima kasih.