Jurnal Suficademic | Artikel No.23 | September 2025
100 TAHUN TGK. HASAN: GAM, DARI “TIRO-ISME” KE “ROTI-ISME”
Bismillahirrahmanirrahim.
HASAN TIRO, itu bukan manusia biasa. Ia pahlawan besar. Tak perlu diakui secara nasional. Ia telah menjadi jiwa bagi Aceh. Wajah perlawanan atas sebuah sistem yang angkuh. Wajah Indonesia yang pernah busuk tidak karuan.
Hasan Tiro itu tokoh agung. Seorang filsuf. ‘Nabi’. Designer sebuah gerakan. Pada sosok semacam itu, pasti ada pemikiran. Ada filosofi. Ada ideologi. Ada semangat. Ada janji yang disampaikan.
Setiap kata-katanya memiliki getaran. Ceramahnya menghipnotis pejuang. Tulisannya membangun identitas kebangsaan. Aura namanya menggerakkan rakyat untuk hidup tanpa keterjajahan.
Aceh beruntung. Ada Hasan Tiro. Bagi Aceh pada masa itu, ia sepenuhnya pencetus perlawanan. Pengingat harga diri dan kebebasan. Peneguh idealisme “Aceh Bak Mata Donja” (New York, 1968). Inspirasi untuk meraih keadilan. Kemerdekaan.
Tapi bagi Republik dimasa itu, tentu saja, ia total pengacau keamanan. Sebagian lain ada yang menyebutnya ‘pedagang’. Lainnya ada yang melabeli sebagai storyteller, mungkin juga pendongeng, yang berhasil memantik semangat rakyat untuk melawan. Sampai Aceh kembali bersimbah darah.
Hasan Tiro adalah generasi terakhir Aceh, yang lantang. Cerdas. Teguh. Berani. Cakap. Diplomatis. Sekaligus militan dalam memperjuangkan apa yang semestinya menjadi hak rakyat. Mungkin juga kesepian dalam pengembaraan. Bercerai. Bahkan ditinggalkan oleh anaknya. Mungkin baginya itulah “The Price of Freedom” (1981).
Itulah Hasan Tiro. Penerus semangat “Tiro”, kaum pejuang terdidik. Tiro adalah perlawanan. Tiro adalah kebebasan. Tiro adalah keberanian. Tiro adalah kerelawanan. Tiro adalah kesyahidan. Tiro adalah pemikiran. Tiro adalah ideologi yang melampaui perut dan kepemilikan. Tiro adalah Tuhan, yang menjelma dalam gerakan keadilan.
***
Hasan Tiro sudah tiada. Seratus tahun setelah kelahirannya (25 September 1925), ide kemerdekaan Aceh yang gigih ia usung sampai pikun, telah disapu gelombang tsunami. Ide Aceh sebagai negara berdaulat sudah di kubur di desa Meureu, Indrapuri. Sekitar 20 km arah timur kota Banda Aceh.
Tokoh besar ini telah 15 tahun tiada. Ia wafat di RSUDZA pada 13 Juni 2010. Banyak misteri diseputar hari-hari terakhirnya. Politik meninggalkan banyak cerita. Ia memang bukan orang suci. Tapi legacy-nya abadi.
Ada satu hal yang menjadi prediksi saya. Mungkin sampai 100 tahun ke depan, di Aceh tidak akan muncul lagi Hasan “Tiro”. Yang akan banyak muncul adalah Hasan “Roti”. Hasan Roti ini teman saya. Minatnya hanya sama roti. Begitulah gambaran fase perjuangan yang fokus telah berubah kepada sepotong ‘Roti’. Seperti kata salah satu teman eks kombatan, “Setelah capek berperang, lapar kita”. Ada benarnya.
Kemerdekaan geografis bangsa Aceh dalam makna sebuah negara, meminjam potongan judul tulisan Hasan Tiro, telah menjadi “unfinished diary”. Semua menjadi cerita yang tidak berujung. Sebuah kisah yang tidak selesai. Sudah tutup buku.
Catatan perjuangan GAM telah diakhiri dengan penyerahan senjata. Diikat dengan MoU Helsinki. Dikunci dalam UUPA. Para kombatan telah bergabung dengan NKRI. Mulai menghormati Merah Putih. Terdengar riuh menyanyikan Indonesia Raya. Mungkin juga sudah menyimpan jauh-jauh bendera Bulan Bintang dalam lemari gudang rumahnya.
Namun demikian, apakah universalisme cita-cita Hasan Tiro telah berakhir?
Wallahu ‘alam!
Mungkin “kemerdekaan” dalam makna ekonomi masih terbuka. Darah pejuang Aceh tentu tidak pernah dingin. Karena itu, perjuangan keadilan tidak pernah putus.
Namun lagi-lagi. Setiap perjuangan butuh ideolog. Perlu filsuf. Butuh pemikir. Harus ada ‘nabi’. Perlu orang cerdik. Perlu jiwa-jiwa yang suci. Harus ada panglima, yang bukan hanya cerdas, tapi juga berani. Yang paling penting, ada Tuhan dalam diri. Inilah makna “kemerdekaan” hakiki.
Yang terakhir inilah yang melahirkan “tiro-isme”. Sosok para pejuang suci. Tanpa Tuhan, yang lahir adalah generasi “roti-isme” an sich. Generasi yang hanya berjuang untuk sepotong roti. Setelah kenyang, diam. Dulu berjuang sama-sama untuk kemerdekaan. Begitu teken MoU, mulai mengejar kesejahteraan masing-masing. Rakyat terabaikan.
Ideologi Hasan “Tiro-isme” melahirkan panglima dan kombatan yang pro rakyat. Pro kemakmuran bersama. Sedangkan Mazhab Hasan “Roti-isme” melahirkan gubernur, dewan, bupati yang pro proyek semata. Gabungan keduanya akan lebih menarik.
Perjuangan paska Hasan Tiro terlihat seperti bergerak dalam ideologi yang tak menentu. Seperti bingung. Setelah merdeka, kita mau kemana. Setelah merdeka, tentu saja semua bangsa akan bekerja untuk sejahtera. Aceh paska MoU juga berusaha meraih itu. Namun, ideologi apa yang akan dipakai. Siapa yang akan lahir dalam fase Aceh terkini. Hasan “Tiro” baru, yang kekeh dengan visi kerakyatan; atau Hasan “Roti” yang sibuk mengejar tumpuk masing-masing?
“The Price of MoU: Dari Tiro-isme ke Roti-isme”. Mungkin itu judul yang tepat untuk melihat Aceh terkini. Di era Hasan Tiro, para kombatan dikejar tentara. Di era Hasan Roti, saya mulai khawatir, jangan-jangan akan ramai kena OTT KPK. Semoga tidak terjadi. Ketika dimensi “Tiro” ditinggalkan, semua eks GAM akan kehilangan ideologi sucinya. Sehingga berubah menjadi kapitalis baru dalam pembangunan. Menjadi ‘Belanda-Belanda’ baru di Aceh.
Namun demikian, perjuangan dari “Tiro” ke “Roti” juga menggambarkan satu hal positif. Tentu ketika keduanya tidak terpisahkan. Lewat ideologi “Tiro” kita terus berzikir untuk memerdekakan diri. Lalu lewat ideologi “Roti” kita bekerja untuk mensejahterakan semua. Tiro dan roti adalah dua sisi dari satu Aceh yang sama. “Tiro” adalah ideologi pembebasan, salah satu akar dari kejuangan Aceh. Sementara “Roti” adalah konsep negara sejahtera. Kombinasi keduanya menjadi semangat bagaimana Aceh menjadi provinsi yang berdaulat, sekaligus sejahtera.*****

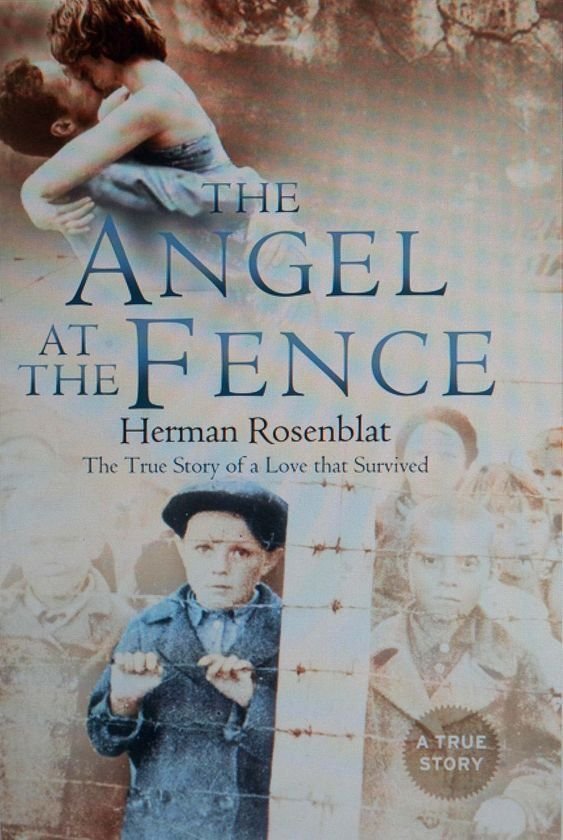

“Hasan Tiru sangat langka”
Indonesia atau mkn dunia harus bsnyak “Hasan Tiro “