Jurnal Suficademic | Artikel No.11 | Agustus 2025
“INCLUSIVE PARADIGM”: KENAPA ILMU TIDAK MEMBEBASKAN?
Oleh Said Muniruddin | Rector Suficademic
Bismillahirrahmanirrahim.
PENDAHULUAN
Usaha untuk memproduksi orang cerdas tidak pernah berhenti. Jumlah sarjana S1 dan D3 lulusan perguruan tinggi di Indonesia pertahun mencapai 1,5 juta (Ditjen Dikti, 2022). Belum termasuk S2 dan S3. Data lainnya menyebut total angka sarjana yang lahir setiap tahun di republik ini mencapai 1,9 juta orang (CNBC Indonesia, 2025). Konon lagi jumlah profesor yang terus meningkat, birokrat yang semakin cerdas, serta politisi yang semakin berpengalaman.
Tapi, kenapa ilmu tidak membebaskan? Kenapa banyak pemilik ilmu hidupnya tidak menjadi lebih baik dan lebih mulia? Juga kenapa masyarakat disekitar orang berilmu kondisinya tidak maju, tertindas dan tidak sejahtera?
Salah satu jawabannya ada pada paradigma dari pengetahuan yang kita miliki.
Paradigma adalah worldview, cara pandang atau keyakinan kita terhadap sebuah realitas dari pengetahuan. Paradigma pengetahuan ada 5: positivis, interpretif, kritis, postmodernis, dan spiritualis. Paradigma ini dapat ditemukan dalam aneka riset kuantitatif dan kualitatif (Merriam & Grenier: 2019, Creswell: 2018, Yin: 2015, Patton: 2014, Triyuwono, 2013, Denzin & Lincoln: 2005, dll). Kelima ini merupakan jenis pengetahuan dari level yang sangat normatif, basic, objektif, rigid dan sempit; sampai kepada pengetahuan yang lebih fleksibel, luas, mencerahkan dan menggerakkan.
Dalam artikel ini, kami akan menelaborasi 5 paradigma ini dalam sebuah konstruksi pengetahuan yang inklusif (inclusive paradigm). Tujuannya untuk melahirkan model manusia yang paripurna lewat ilmu pengetahuan (insan kamil).
PARADIGMA PENGETAHUAN
Pertama, paradigma “positivis”.
Sebagian orang berilmu pada level positivis. Dia melihat ilmu hanya sebatas ilmu. Ilmu itu hanya sebatas data ataupun informasi. Ilmu itu hanya sebuah produk yang dihasilkan dari proses observasi terhadap fenomena alam. Tidak salah. Sebab, kita memang disuruh mengamati secara inderawi: “afala tubshirun” (tidakkah kamu melihat?) “afala tasma’un” (tidakkah kamu mendengar?).
Pada level positivisme, ilmu itu hanya wujud material dari angka, statistik, teks, kalimat, kata dan bahasa yang ia temukan dari proses penelaahan empirik. Kaku memang (‘objektif’). Mungkin tanpa nyawa sama sekali. Ilmu itu berjarak, sesuatu yang berada di luar dirinya. Berilmu pada level ini, ya hanya untuk sekedar tau. Sudah tau, ya sudah berilmu. Paling tidak, ilmu yang ia ketahui dan kuasai hanya menjadi alat teknis prosedural untuk mengerjakan sesuatu.
Ketika dia sekolah, ia hanya melihat ilmu sebatas alat untuk menyelesaikan sebuah persoalan teknis. Seorang akuntan, melihat ilmu akuntansi hanya sebagai alat untuk membuat laporan keuangan. Seorang dokter, melihat ilmu bedah hanya sebagai alat untuk memotong organ manusia. Seorang arsitek, hanya melihat ilmu arsitektural hanya sebagai alat untuk mendesain rumah dan gedung. Begitu juga ilmu-ilmu lainnya.
Si pemilik ilmu, pada akhirnya hanya menjadi alat bagi industri untuk membuat laporan keuangan, memantau isi perut orang, membangun struktur dan lainnya sebagainya. Manusia adalah buruh, mesin. Hari ini, pekerjaan semacam ini sudah diambil alih oleh robot. Orang-orang pada level paradigma pengetahuan semacam ini hanya hidup untuk mencari hidup (mencari uang). Ilmu itu teknis untuk mengumpulkan uang. Kapitalisme tumbuh subur dalam paradigma ilmu semacam ini. Karenanya, modernisme sangat dipengaruhi oleh positivisme-empirisme. Orang kehilangan ruh dan makna dalam hidup.
Kedua, paradigma “interpretif”.
Pada level ini, ilmu bukan lagi angka, data dan kalimat semata. Melainkan ada makna. Mulai ada rasa. Mulai ada interpretasi atas informasi dan pengetahuan yang ia dapatkan. Pengetahuan mulai masuk dalam dirinya. Mulai tidak ada jarak antara ia dengan objek yang diketahui. Ia mulai menganalisis, apa makna dari sesuatu yang ia ketahui. Apa maksud kemiskinan Aceh sebesar 12,33 persen tahun 2025? Apa makna dana Otsus 100 trilyun yang sudah dinikmati Aceh selama 16 tahun (2008-2024)? Itu kasus Aceh. Anda bisa menarik ini pada kasus lokal daerah masing-masing. Ataupun kasus-kasus nasional.
Pada tahap ini; ia mulai sadar. Ia mulai memahami; angka, data dan laporan mengandung pesan yang dalam. Ada cerita dari semua itu. Jiwanya mulai berbicara dan mengungkap makna-makna. Pada level ini, potensi akalnya mulai terbuka: “afala ta’qilun” (apakah kamu tidak mengerti?).
Ketiga, paradigma “kritis”.
Pada level kritis, Anda akan masuk pada pemahaman lebih mendalam: “afala yatafakkarun” (apakah kamu tidak berpikir?). Daerah Anda memiliki data statistika kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pengangguran dan lainnya sedemikian rupa; itu bukan sebuah kejadian independen. Angka-angka itu tidak lahir dari ruang hampa. Itu bukan kehendak alam. Itu bukan murni keinginan Tuhan. Itu semua terjadi akibat ulah tangan manusia.
Pengetahuan pada level ini akan berusaha menangkap akar dari persoalan. Setiap masalah yang timbul dimuka bumi, ada hubungannya dengan struktur sosial, dinamika kekuasaan dan ideologi yang berkembang. Ada aktor yang menyebabkan kehancuran terjadi. Ada agen-agen yang bekerja secara keliru atau mungkin curang, sehingga pembangunan menjadi mundur atau stagnan. Setiap ada persoalan pada angka statistik, akan dicari siapa dalang semua itu.
Pengetahuan pada level ini sudah mulai “investigatif”. Anda harus berusaha menemukan siapa iblis, siapa setan, siapa sosok kriminal yang bertanggung jawab atas kerusakan di muka bumi. Atau sebaliknya, siapa “malaikat” yang menyebabkan negeri atau daerah Anda semakin maju dan sejahtera.
Ini yang namanya pengetahuan “kritis”. Seorang pengamat ekonomi, sebaiknya tidak berhenti pada pemaparan data ekonomi. Anda harus masuk ke makna dari data. Lebih jauh lagi, Anda harus menemukan siapa “bandit” yang bertanggung jawab terhadap itu semua. Banyak akademisi takut untuk masuk pada level kritis semacam ini. Masalahnya bukan tidak berilmu. Tapi ketakutan. Memang, tidak semua orang berilmu, itu berani. Perubahan tidak terjadi hanya dengan sekedar memaparkan data normatif. Seminar semacam itu tidak membawa perubahan.
Banyak sekali skripsi, tesis dan disertasi yang terhenti di temuan positivistik. “Anggaran X, Y, Z tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan”, kesimpulan positiv-objektifnya seperti itu. So what? Tak ada kelanjutan. Selesai sampai disitu. Masuk Scopus. Jadi doktor, jadi sarjana Anda. Tidak ada makna lebih dalam dari temuan itu. Juga tak ada tindakan apapun yang dilakukan untuk membereskan itu. Tak ada gerakan yang lahir dari sebuah pengetahuan baru.
Seharusnya, intelektual itu menjadi ideolog dalam menginisiasi kesadaran awam. Kaum cendekiawan harus terhubung dengan kelas-kelas sosial. Mereka harus bisa menggerakkan massa dan kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya, untuk secara “amar makruf” memperbaiki kondisi sosial mereka lewat program-program pengabdian. Ataupun secara “nahi munkar” berani memimpin rakyat untuk memaksa figur-figur pada sektoral kekuasaan tertentu, agar bekerja secara adil dan benar.
Pada tahap inilah diperlukan dialog, demontrasi, reformasi bahkan revolusi. Mungkin juga dengan secara simbolik mengibarkan bendera “One Piece”, sebagai bentuk protes dan perlawanan. Berawal dari data, yang diinterpretasi, berlanjut pada gerakan untuk memperbaiki struktur kekuasaan agar ke depan kondisi menjadi lebih baik. Seringkali kekuasaan itu despotis, tuli dan buta. Pelu cara-cara kreatif untuk menyadarkannya.
Hakikat kampus sebenarnya untuk itu. Kampus punya kemampuan untuk me-regress dan memproduksi data. Kampus punya juga profesor doktor untuk memaknai itu. Kampus juga punya pasukan mahasiswa untuk meneriakkan perubahan yang berbasis analisis data. Sayangnya, ruh kritis ini sudah mulai mati di kampus-kampus. Kampus sudah senyap. Sudah berubah menjadi industri produksi sarjana. Mahasiswanya tidak lagi diajak berpikir kritis terhadap ketimpangan dalam struktur sosial. Dosennya sudah sibuk dengan aktifitas positivisme-administratif. Kampus tidak lagi menjadi pemikir otonom. Tidak lagi menjadi “jantung hati” yang memompa darah dan kesadaran bagi rakyatnya.
Keempat, paradigma “postmodernis”.
Pada level ini, pertanyaan epistemologisnya adalah: “afala tadabbarun” (apakah kamu tidak merenung?). Proses belajar adalah proses mendekonstruksi pengetahuan. Bahwa realitas tidak berdiri sendiri. Semua saling terkait. Banyak variabel yang harus ditemukan untuk merakit sebuah pemahaman. Segala sesuatu harus di evaluasi kembali. Realitasnya harus dipahami, didekonstruksi ulang.
Proses belajar adalah proses untuk memahami aneka kejadian dalam sejarah, aneka pola yang berkembang, aneka fenomena yang terjadi; guna memahami pengaruhnya terhadap sesuatu. Sebuah ilmu tidak berdiri sendiri. Semua saling terkait. Sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, agama dan lainnya; itu satu kesatuan. Semakin multiparadigma dan semakin interdisiplin sebuah ilmu; maka semakin kuat ia menjelaskan wujud dari sebuah realitas.
Modernisme membuat manusia menjadi terasing. Modernitas membuat manusia menjadi makhluk materi. Postmodernis berusaha mendekonstruksi. Bahwa manusia juga makhluk multidimensi. Melihat manusia tidak boleh hanya sebagai makhluk bumi. Tapi juga sebagai makhluk langit. Manusia bukan atom an sich. Manusia juga makhluk kuantum.
Pemahaman ini membawa manusia kepada pengetahuan yang holistik dan terintegrasi. Kita harus melihat manusia yang bersuku sebagai satu, sebagai heterogenitas organ dari satu wujud yang sama. Isu imperialisme terhadap Palestina bukan isu muslim semata. Melainkan isu kemanusiaan secara global. Realitas itu pada hakikatnya “satu” (Tauhid, the Oneness). Pada konsepsi ini, pembangunan harus bersifat lintas sektoral. Melihat kemiskinan tidak hanya problem dinas sosial saja. Melainkan juga masalah yang timbul dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Seorang ilmu harus bisa melihat masalah dari berbagai sisi. Juga harus mampu mengumpulkan semua stakeholder pembangunan untuk duduk menuntaskan sebuah masalah secara bersama.
Level ini lebih tinggi dari “kritisme”. Anda boleh kritis terhadap pemerintah. Tapi ketika Anda mengkritik dan mendemo pemerintah, pada hakikatnya Anda sedang berusaha memperbaiki diri sendiri. Anda melihat pemerintah sebagai diri Anda sendiri, yang harus Anda perbaiki. Yang harus Anda reformasi. Anda kritis, sekaligus dekat dengan pemerintah. Seperti hubungan ayah dengan anak. Sayang, tapi tegas. Bila perlu, kalau terlalu bandel, ‘pukul’ sedikit. Bakar ban. Pecahin satu dua kaca. Di demo aja. Lalu ngopi bareng lagi.
Kelima, paradigma “spiritualis”.
Ini paradigma pengetahuan tertinggi: “afala tadzakkarun” (apakah kamu tidak menyatu dalam ingatan kepada-Nya?). Ini sudah level wahdatul wujud. Atau mungkin wahdatusy syuhud. Anda sudah lebur dalam ke-Esa-nya. Tidak ada lagi (kesadaran egoistis) Anda. Yang ada hanya (kesadaran) ketuhanan saja.
Pada tahap spiritual ini, berpikir dan bertindak sudah melalui kesadaran Ilahi. Anda tidak merasa tau. Tuhanlah yang tau. Anda tidak bergerak. Tuhanlah yang bergerak. Ini kesadaran para nabi, para wali. Anda bisa meminjamnya. Pada makam ini Anda sudah bekerja berdasarkan kesucian Asma Tuhan. Sudah menjadi khalifah-Nya. Karena itu, perubahan ke arah kebaikan pasti terjadi. “Kun, fayakun!”.
Pengetahuan pada level ini sudah berbeda jauh dengan paradigma “positivisme”. Positivisme menganggap Tuhan sebagai “objek” sekuler di luar diri kita. Tuhan adalah sesuatu yang haru diamati di ‘langit’ sana. Sedangkan paradigma spiritualis telah menyadari bahwa Dia adalah wujud pengetahuan dan kesadaran yang menyatu dalam diri kita. Dia lebih dekat dari urat leher. Tuhan adalah CCTV yang melekat dalam kesadaran Anda. Jika ini terjadi, transformasi diri dan pembangunan akan mengalami gerak multiplier yang bersifat infinity.
KESIMPULAN
Paradigma pengetahuan ada 5. Masing-masing dari level kesadaran terendah ke yang tertinggi. Namun, kelimanya tidak boleh dipisah. Semuanya adalah satu kesatuan paradigma yang harus dimiliki oleh setiap ilmuan dalam mewujudkan keutuhan manusia. Paradigma tersebut adalah: (1) Tubshirun/Taf’alun -positivistik; (2) Ta’qilun -interpretif; (3) Tafakkarun -kritis; (4) Tadabbarun -postmodernis; ,(5) Tadzakkarun -spiritualis. Gabungan kelima paradigma tersebut, dalam artikel ini kami sebut “inclusive paradigm”.
Itu hanya paradigma, keyakinan, cara pandang, atau belief system terhadap sebuah realitas pengetahuan. Untuk menciptakan perubahan, maka harus ada satu hal lagi yang harus dipenuhi. Yaitu “sistem tindakan”. Para nabi pada awalnya hadir untuk mendidik manusia untuk membuat manusia punya makrifat terhadap 5 level paradigma pengetahuan ini. Tapi puncak makrifat dan syahadah, itu ada pada “mujahadah” (jihad/gerak/tindakan).
Nabi bukan hanya hadir untuk mengajar ilmu. Tapi juga memimpin komunitasnya untuk “mengasah pedang”. Perubahan terjadi ketika ilmu ditransfer dalam ruang juang. Kalau dalam bahasa sekarang, jangan cuma cerdas dan beriman doang. Jangan cuma hafal Quran dan hadis doang. Tapi harus seperti Iran, mampu merudal dan membuat Tel Aviv berantakan. Kalau semua negara Arab begitu, sudah pasti Baitul Maqdis bisa segera dibebaskan dari tangan zionisme.
Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa Aali Muhammad.*****

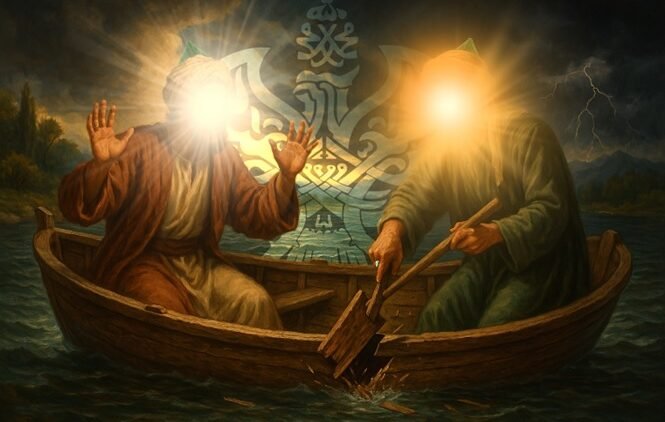

keren bapak … semoga istiqomah menyampaikan hal hal yang mencerahkan yaa
Alright mate, just clocked bmw555login. Seems decent enough for a quick spin. Fingers crossed for some luck though. Check it out yourself bmw555login.
I recently visited 66bgame and I was impressed with their gaming selection. Their easy-to-navigate website provides a user experience that keeps bringing me back! See what they offer: 66bgame
Yo, 188betag is where it’s at! Been using it for a while now and haven’t had any issues. Quick payouts and responsive customer support. Good place to throw down a few bets. Highly recommend! 188betag
Spicy 04? Nghe là thấy cay rồi đó nha. Chắc là toàn kèo thơm kèo cháy. Anh em nào thích ăn cay thì vào đây mà chiến. Jump in spicy 04.